
Abstrak
Dalam beberapa tahun terakhir pengadilan Inggris dan Wales telah mengakui iterasi baru dari tinjauan yudisial yang dalam artikel ini disebut ‘tinjauan implementasi kebijakan yang tidak tepat dari perjanjian’ atau ‘RIPIT’. RIPIT memungkinkan pengadilan peninjau untuk meneliti dokumen kebijakan dalam negeri yang diumumkan untuk tujuan mengamankan kepatuhan dengan perjanjian yang tidak tergabung secara legislatif untuk konsistensinya dengan perjanjian itu. Artikel ini membahas kemunculan RIPIT dan membelanya terhadap keberatan penting yang mungkin ditujukan kepadanya: yaitu bahwa, dengan terlibat dalam RIPIT, pengadilan bertindak tidak konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai penggunaan perjanjian yang tepat secara hukum dalam sistem hukum ‘dualis’ Inggris Raya. Artikel ini berpendapat bahwa, jika dipahami dengan benar, RIPIT memerlukan penerapan doktrin tinjauan yudisial yang mapan dengan cara yang sepenuhnya konsisten dengan prinsip konstitusional dan yurisprudensi yang mapan. Namun, munculnya RIPIT memberikan kesempatan berharga untuk merenungkan kesesuaian beberapa cara umum dalam mengekspresikan hubungan antara perjanjian, hukum Inggris, dan pengadilan domestik, termasuk istilah ‘dualisme’ itu sendiri.
PERKENALAN
Sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika pemerintah Inggris meratifikasi perjanjian internasional, tindakan ratifikasi itu sendiri tidak serta merta memperkenalkan standar hukum baru ke dalam hukum nasional. 1 Dalam pengertian itu, perjanjian, sebagaimana yang dikatakan Lord Oliver, tidak ‘berlaku dengan sendirinya’. 2 Sebaliknya, jika pemerintah ingin memastikan kepatuhan terhadap perjanjian, pemerintah perlu mengambil langkah lebih lanjut. Merupakan hal yang umum bagi pemerintah untuk memberlakukan undang-undang 3 melalui parlemen. Berbagai pendekatan terhadap penyusunan undang-undang dapat dan telah diambil. 4 Undang-undang dapat secara langsung ‘memasukkan’ ketentuan perjanjian ke dalam hukum Inggris, yang pada dasarnya memberikan mandat hukum kepada pengadilan nasional untuk menafsirkan, menerapkan, dan menegakkannya. 5 Undang-undang juga dapat menerapkan perjanjian secara lebih tidak langsung, seperti dengan menciptakan kewajiban hukum baru atau fungsi badan publik yang dirancang untuk memajukan tujuan perjanjian. 6
Akan tetapi, membuat undang-undang bukanlah satu-satunya pilihan. Terkadang 7 pemerintah mungkin lebih suka menyusun dan mengedarkan pedoman kebijakan. 8 Cara ini mungkin tampak sangat tepat jika suatu perjanjian terutama mengharuskan tindakan oleh otoritas publik: kebijakan pelaksanaan kemudian dapat berbentuk instruksi operasional, yang mengarahkan pejabat untuk melaksanakan fungsi mereka sesuai dengan perjanjian. Dibandingkan dengan membuat undang-undang, pengumuman kebijakan mungkin tampak lebih sederhana dan cepat.
Dalam konteks inilah pertanyaan hukum penting telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Yaitu, apakah, dalam menyusun kebijakan yang dimaksudkan untuk memberlakukan suatu perjanjian, pemerintah secara hukum diharuskan untuk memastikan konsistensi antara keduanya. Atau, untuk menyatakan hal yang sama dengan cara lain, apakah pemohon dalam proses peninjauan kembali yudisial dapat menantang kebijakan pelaksanaan perjanjian atas dasar bahwa kebijakan tersebut tidak mampu mengamankan kepatuhan terhadap perjanjian yang dimaksudkan untuk dilaksanakan. Pengadilan baru-baru ini dan berulang kali bergulat dengan pertanyaan ini. Jawaban yang diberikan sejauh ini adalah ‘ya’. Jadi, yang paling penting, dalam R (EOG/KTT) v Secretary of State for the Home Department 9 ( EOG/KTT ), Pengadilan Banding memutuskan bahwa pedoman Home Office melanggar hukum karena didasarkan pada kesalahpahaman tentang Council of Europe Convention Against Trafficking (ECAT), 10 perjanjian yang tidak dimasukkan secara legislatif.
Yurisprudensi ini melihat munculnya iterasi baru 11 tinjauan yudisial yang dalam artikel ini disebut ‘tinjauan atas penerapan kebijakan perjanjian yang tidak tepat’ atau ‘RIPIT’. Hingga saat ini, RIPIT hanya mendapat sedikit perhatian akademis. 12 Kelalaian ini mungkin sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa RIPIT belum menjadi fokus banding di Mahkamah Agung Inggris 13 dan bahwa yurisprudensi hingga saat ini memiliki karakteristik yang mencolok. Yaitu, ia secara eksklusif menyangkut keabsahan kebijakan Inggris terhadap korban perdagangan manusia. Kedua fitur ini mungkin membuat RIPIT agak ‘tidak terlihat’ 14 bagi para komentator.
Pengabaian RIPIT sangat disayangkan karena berbagai alasan. Pertama-tama, karena ada potensi keberatan penting terhadap RIPIT yang harus dianalisis secara menyeluruh. Merupakan asas hukum tata negara Inggris yang mapan bahwa eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hukum dalam negeri secara sepihak, termasuk melalui pelaksanaan hak prerogatifnya untuk meratifikasi perjanjian. 15 Sebagai konsekuensi asas ini, sering dikatakan bahwa pengadilan pada umumnya diharuskan untuk menganggap perjanjian yang tidak berbadan hukum sebagai ‘tidak dapat diadili.’ 16 Seperti yang dikatakan Lord Denning, hakim pada umumnya tidak boleh ‘memperhatikan perjanjian sampai perjanjian tersebut dituangkan dalam undang-undang yang disahkan oleh Parlemen.’ 17 Dengan latar belakang ini, RIPIT mungkin tampak mencurigakan secara konstitusional. Pertanyaan utama dalam kasus RIPIT, bagaimanapun juga, adalah apakah dokumen kebijakan dalam negeri sesuai dengan perjanjian yang tidak berbadan hukum. Kepatuhan terhadap perjanjian, secara sederhana, adalah inti hukum dari kasus-kasus ini.
Salah satu tujuan artikel ini adalah untuk menarik perhatian para pengacara publik terhadap munculnya RIPIT, dan, mudah-mudahan, untuk memicu perdebatan. Tujuan utama lainnya adalah untuk membela RIPIT terhadap keberatan dari prinsip konstitusional yang baru saja diuraikan. Bagian berikutnya menelusuri kemunculan RIPIT melalui sekumpulan hukum kasus yang penting, tetapi sebagian besar diabaikan. Bagian ketiga menjelaskan keberatan konstitusional secara lebih mendalam. Tiga bagian berikutnya kemudian menawarkan tanggapan tiga bagian yang terperinci.
Keempat menyoroti bahwa ketidakmampuan eksekutif untuk mengubah hukum domestik secara sepihak tidak berarti bahwa perjanjian sama sekali tidak relevan secara hukum. Standar hukum domestik dapat, dan telah lama, membuat perjanjian relevan dengan penyelesaian sengketa hukum domestik dalam berbagai cara. Bagian kelima berpendapat bahwa, dalam yurisprudensi RIPIT, ada standar seperti itu yang berlaku: yaitu, prinsip peninjauan kembali yudisial yang mapan yang mengharuskan kriteria suatu kebijakan untuk secara wajar mampu memenuhi tujuan yang diumumkannya (disebut di sini sebagai ‘ prinsip ABCIFER ‘ 18 ). Pengadilan yang terlibat dalam RIPIT tidak, seperti yang diperdebatkan, terlibat dalam peninjauan terhadap ketentuan perjanjian itu sendiri. Pengadilan menerapkan prinsip ABCIFER pada konteks spesifik suatu kebijakan yang dimaksudkan untuk menerapkan suatu perjanjian. Bagian keenam menjelaskan mengapa tidak ada yang bermasalah atau tidak biasa tentang standar hukum umum, daripada undang-undang, yang menyediakan ‘pijakan’ hukum 19 untuk suatu perjanjian dengan cara ini. Tidak hanya beberapa ‘pijakan’ hukum domestik yang paling dikenal untuk perjanjian merupakan produk dari standar hukum umum, tetapi juga sepenuhnya diperbolehkan bagi pengadilan untuk mengembangkan hukum umum dengan cara yang membuat perjanjian relevan secara hukum dengan cara baru. RIPIT, secara sederhana, adalah contoh modern dari hal ini.
Dua bagian terakhir, akhirnya, menawarkan beberapa refleksi yang lebih luas dan penutup. Bagian ketujuh berpendapat bahwa munculnya RIPIT memberikan kesempatan yang berharga untuk merenungkan manfaat dari beberapa bahasa yang sekarang umum digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perjanjian, hukum domestik, dan pengadilan Inggris. Secara khusus, bagian ini menyatakan bahwa istilah ‘dualisme’ tidak diperlukan atau berisiko menyesatkan, dan oleh karena itu hakim dan komentator sebaiknya menjauhinya. Bagian kedelapan kemudian menyimpulkan dengan mempertimbangkan secara singkat prospek RIPIT untuk bertahan dari banding ke Mahkamah Agung Inggris.
MUNCULNYA RIPIT
Bagian ini menguraikan kemunculan RIPIT dalam serangkaian yurisprudensi terkini yang penting. Seperti yang ditekankan di atas, yurisprudensi sejauh ini secara eksklusif berkaitan dengan tantangan terhadap kebijakan perdagangan manusia di Inggris. Penting untuk diperjelas bahwa RIPIT tidak terbatas pada konteks administratif ini. Namun, fitur yurisprudensi ini berarti bahwa akan bermanfaat untuk memulai dengan beberapa pernyataan pengantar tentang hukum dan kebijakan yang mengatur pengambilan keputusan perdagangan manusia di Inggris.
‘Perdagangan manusia’ dan istilah terkait ‘perbudakan modern’ terkenal sarat dengan ketidaktepatan. 20 Tidak seperti definisinya, status perdagangan manusia sebagai masalah global yang besar sudah sangat jelas. Misalnya, pada tahun 2021, Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan bahwa terdapat 50 juta orang di seluruh dunia yang mengalami perbudakan modern setiap harinya, yang berarti hampir satu dari setiap 150 orang. 21
Di tingkat internasional, perdagangan manusia menjadi fokus sejumlah perjanjian. 22 Di antara yang paling penting adalah ECAT. 23 ECAT memiliki ‘fokus kuat pada peradilan pidana’ 24 dan banyak ketentuannya menyangkut hukum pidana substantif 25 dan prosedural 26 domestik . Namun, ECAT lebih dari sekadar perjanjian hukum pidana. Di antaranya, perjanjian ini memuat serangkaian ketentuan yang berkaitan dengan identifikasi dan perlindungan korban. Secara khusus, Pasal 10 mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah administratif, termasuk dengan membentuk ‘otoritas yang kompeten’ untuk mengidentifikasi korban. Pasal 12–14 menciptakan serangkaian tugas untuk menyediakan berbagai bentuk dukungan negara.
Di tingkat domestik, Mahkamah Agung Inggris telah menyatakan bahwa ‘ECAT sebagaimana adanya belum dimasukkan ke dalam hukum Inggris [tetapi] kewajibannya telah dilaksanakan melalui berbagai langkah.’ 27 Pernyataan ini menangkap poin bahwa, tidak seperti beberapa perjanjian, 28 tidak ada tindakan parlemen yang memberikan efek hukum domestik pada ECAT secara keseluruhan. Sebaliknya, kepatuhan terhadap ECAT diupayakan melalui berbagai inovasi yang berbeda. Beberapa, seperti Undang-Undang Perbudakan Modern 2015, bersifat legislatif. 29 Namun, pendekatan yang agak berbeda telah diambil terhadap ketentuan dukungan korban ECAT. Alih-alih mengadopsi undang-undang, pemerintah Inggris terutama ‘berusaha untuk memenuhi [kewajiban ini] … melalui kebijakan eksekutif, terutama Mekanisme Rujukan Nasional’ 30 atau ‘NRM’.
NRM diperkenalkan melalui penyesuaian praktik administratif pada tahun 2009. Ini adalah proses terpusat, yang sekarang dikelola oleh dua unit spesialis di dalam Kementerian Dalam Negeri. 31 Setelah seseorang dirujuk ke sistem oleh organisasi penanggap pertama, ada dua tahap. Awalnya, keputusan dibuat mengenai apakah ada ‘alasan yang wajar’ untuk meyakini bahwa mereka adalah korban. Jika demikian, keputusan ‘alasan konklusif’ akan menyusul. Pengoperasian NRM disusun oleh panduan Kementerian Dalam Negeri yang telah melalui banyak amandemen. Versi saat ini, Perbudakan Modern: panduan hukum untuk Inggris dan Wales , 32 memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Perbudakan Modern 2015. 33
Kecukupan NRM, dan inisiatif antiperdagangan manusia lainnya di Inggris, 34 telah menjadi subjek kritik yang kuat dan berkelanjutan. 35 NRM telah diganggu oleh penundaan yang sangat parah. 36 Sebagai indikasi, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan dasar yang konklusif antara April dan Juni 2023 adalah 451 hari, turun dari 565 hari pada kuartal sebelumnya. 37 Lebih jauh lagi, kebijakan imigrasi pemerintah Inggris yang bermusuhan 38 telah menyebabkan banyak individu di dalam NRM tidak memenuhi syarat untuk bekerja 39 dan penyediaan dukungan yang didanai publik sangat tidak konsisten. 40
Oleh karena itu, mungkin tidak mengherankan jika pengadilan telah mempertimbangkan serangkaian tantangan tinjauan yudisial yang berkaitan dengan aspek-aspek NRM. Motivasi banyak dari tantangan ini adalah kekhawatiran bahwa pedoman kebijakan Kementerian Dalam Negeri tidak mematuhi huruf dan semangat ECAT. 41 Akan tetapi, sebagai masalah hukum domestik, sudah mapan bahwa pelanggaran perjanjian itu sendiri bukanlah dasar yang diizinkan untuk tantangan hukum. 42 Sebaliknya, suatu perjanjian hanya relevan secara hukum sejauh standar hukum domestik membuatnya demikian. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah ada asas hukum domestik yang mengharuskan Menteri Dalam Negeri, dalam menyusun pedoman NRM, untuk memastikan bahwa pedoman tersebut mencerminkan makna ECAT dengan tepat. Jawaban yang diberikan secara konsisten hingga saat ini adalah ‘ya’.
Kasus signifikan paling awal adalah R (Atamewan) v Secretary of State for the Home Department 43 ( Atamewan ): tantangan yang berhasil terhadap sempitnya definisi ‘korban’ dalam pedoman NRM. Ciri terpenting dari kasus ini adalah bahwa penasihat hukum untuk Kementerian Dalam Negeri menerima bahwa, karena maksud Kementerian Dalam Negeri dalam mengumumkan pedoman tersebut adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ECAT, pedoman tersebut akan melanggar hukum sejauh pedoman tersebut gagal melakukannya. ‘ Pengakuan Atamewan ‘ ini, 44 sebagaimana yang dikenal, telah berulang kali diandalkan sejak saat itu. 45 Sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung Inggris dalam MS (Pakistan) v Secretary of State for the Home Department , Menteri Dalam Negeri secara umum, ‘menerima bahwa … akan menjadi kesalahan hukum yang dapat diadili jika NRM tidak secara akurat mencerminkan persyaratan ECAT’. 46
Akan tetapi, ada dua kesempatan di mana dasar hukum RIPIT telah menerima pertimbangan yudisial yang eksplisit. Pertama, R (Galdikas) v Secretary of State for the Home Department pada tahun 2016. 47 Menyimpang dari praktik yang biasa mengandalkan konsesi Atamewan , Home Secretary berpendapat bahwa terlibat dalam RIPIT akan tidak konsisten dengan otoritas terkemuka 48 tentang hubungan antara hukum perjanjian domestik dan hukum perjanjian yang tidak tergabung secara legislatif. Sir Stephen Silber menolak argumen ini pada dasarnya karena dua alasan. Pertama, Mahkamah Agung Inggris telah menetapkan prinsip hukum domestik di Mandalia v Secretary of State for the Home Department 49 ( Mandalia ) yang mengharuskan otoritas publik untuk memberlakukan kebijakan yang ditetapkan tanpa alasan yang kuat. 50 Prinsip ini dikatakan mengharuskan pengadilan untuk terlibat dalam RIPIT, untuk memeriksa apakah konten dokumen kebijakan menyimpang dari ‘kebijakan’ pemerintah Inggris untuk mematuhi ECAT. 51 Kedua, tidak ada satu pun otoritas terkemuka mengenai (tidak)relevansinya perjanjian yang tidak berbadan hukum yang menghalangi pengadilan untuk menerapkan asas hukum domestik ini. Alasan ini (yang akan dibahas secara terperinci di bawah) sepenuhnya didukung dalam kasus penting kedua, yaitu sidang Pengadilan Tinggi dalam perkara R (KTT) v Secretary of State for the Home Department 52 ( KTT ). Linden J juga menyatakan bahwa posisi hukum yang diartikulasikan oleh Sir Stephen Silber tidak diubah 53 oleh putusan Mahkamah Agung Inggris yang lebih baru dalam perkara R (SC) v Secretary of State for Work and Pensions 54 ( SC ) (juga dibahas di bawah).
Baru-baru ini, RIPIT diajukan ke Pengadilan Banding dalam EOG/KTT . 55 Banding gabungan tersebut menyangkut keabsahan pedoman pemberian izin tinggal bagi korban perdagangan manusia yang diduga dan yang telah dikonfirmasi. Meskipun mengajukan keberatan atas masalah tersebut di Pengadilan Tinggi dalam KTT , dan memperoleh izin untuk mengajukan argumen dalam EOG , Menteri Dalam Negeri akhirnya mengandalkan pengakuan Atamewan . Namun, dalam memberikan putusan untuk pengadilan, Underhill LJ, menyatakan dirinya sepenuhnya yakin dengan alasan sebelumnya dari Sir Stephen Silber dan Linden J. 56
Yang penting, Underhill LJ selanjutnya menawarkan panduan terperinci tentang hakikat RIPIT. Menurut panduan ini, RIPIT mengharuskan pengadilan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, apakah panduan yang sedang ditinjau ‘dalam hal-hal yang relevan dimaksudkan … untuk memberlakukan persyaratan’ 57 ketentuan perjanjian. Di sini, pengadilan tidak meragukan bahwa sejarah dan bahasa panduan NRM, 58 ditambah dengan pernyataan saksi departemen, 59 menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ECAT. Kedua, apakah panduan ‘sebenarnya memang demikian’. 60 Pada tahap ini, tantangan dalam EOG ditolak atas dasar bahwa panduan tersebut konsisten dengan kewajiban yang pada dasarnya ‘negatif’ 61 dalam Pasal 10(2) ECAT untuk tidak memindahkan korban yang diduga. Sebaliknya, dalam KTT pengadilan memutuskan bahwa panduan yang berkaitan dengan korban yang dikonfirmasi didasarkan pada salah tafsir Pasal 14(1). 62
Kasus ini memberikan kewenangan yang kuat pada usulan bahwa pengadilan peninjau kini dapat terlibat dalam RIPIT. Iterasi peninjauan ini memungkinkan pengadilan untuk meninjau kebijakan yang telah diumumkan dengan maksud untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional atas konsistensinya dengan perjanjian tersebut. Meskipun yurisprudensi hingga saat ini telah menyangkut pedoman NRM, ini bukanlah iterasi peninjauan yudisial yang, pada hakikatnya, terbatas demikian. Pemicu peninjauan adalah keberadaan kebijakan yang dimaksudkan oleh perancangnya untuk memberlakukan suatu perjanjian. Hal ini mungkin berlaku untuk banyak kebijakan di luar NRM. Tampaknya juga mungkin, jika tidak mungkin, bahwa pemerintah Inggris akan semakin melihat dokumen kebijakan sebagai sarana untuk mencapai kepatuhan terhadap perjanjian sebagai bagian dari pola yang lebih luas dengan mengandalkan kebijakan, daripada undang-undang, untuk memberlakukan perubahan kebijakan jika memungkinkan. 63
Akan tetapi, perlu dicatat bahwa prospek keberhasilan pemohon dalam tantangan RIPIT akan dibatasi secara signifikan oleh setidaknya satu aspek penting dari kerangka kerja yang dinyatakan dalam EOG/KTT . Secara khusus, kebutuhan pemohon untuk membuktikan bahwa kebijakan yang sedang ditinjau diumumkan untuk tujuan khusus guna mengamankan kepatuhan terhadap perjanjian. Para pemohon dapat menunjukkan hal ini dalam EOG/KTT dengan menunjukkan sejarah penyusunan NRM secara khusus. Akan tetapi, tampaknya jelas bahwa sekadar tumpang tindih antara pokok bahasan yang dibahas oleh suatu perjanjian dan oleh kebijakan dalam negeri tidak akan cukup untuk memicu RIPIT.
KEBERATAN KONSTITUSI TERHADAP RIPIT?
Fitur mencolok dari RIPIT adalah bahwa ia mengharuskan pengadilan, dalam proses peninjauan kembali, untuk menggunakan perjanjian yang tidak tergabung dalam undang-undang secara signifikan. Di seluruh kasus hukum yang dibahas di bagian sebelumnya, pertanyaan utama bagi pengadilan adalah apakah isi NRM sesuai atau tidak dengan ketentuan ECAT. Fitur RIPIT ini menimbulkan keberatan yang penting dan jelas. Yaitu bahwa RIPIT tampaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip penting dan mapan hukum tata negara Inggris yang membatasi penggunaan hukum yang dapat dilakukan terhadap perjanjian.
Prinsip pertama semacam itu sudah sangat mapan. Prinsip ini menolak kekuasaan eksekutif untuk mengubah secara sepihak isi hukum domestik, 64 termasuk melalui pelaksanaan kekuasaan prerogatifnya. Ini adalah prinsip dengan sejarah panjang dan telah ditegaskan berkali-kali. 65 Dalam R (Bancoult) v Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (No 2) , misalnya, Lord Hoffmann mengamati bahwa ‘sejak abad ke-17 hak prerogatif tidak lagi memberi wewenang kepada Mahkota untuk mengubah hukum umum atau hukum perundang-undangan Inggris.’ 66 Baru-baru ini, mayoritas dalam R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union ( Miller ) menegaskan kembali bahwa ‘kekuasaan legislatif Mahkota saat ini hanya dapat dilaksanakan melalui Parlemen.’ 67
Kadang-kadang dikatakan bahwa asas tersebut ada untuk menjaga supremasi legislasi parlemen. Dalam Miller , misalnya, Lord Neuberger menggambarkan ‘sistem dualisme Inggris [sebagai] akibat wajar yang diperlukan dari kedaulatan Parlemen atau, dengan kata lain, asas tersebut ada untuk melindungi Parlemen, bukan menteri.’ 68 Sudah pasti bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk mengubah secara sepihak isi hukum domestik mencegah undang-undang parlemen dirusak oleh pelaksanaan kekuasaan prerogatif. 69 Namun, alasan ini tidak dapat memberikan penjelasan yang lengkap. Itu karena asas tersebut tidak hanya mencegah eksekutif menggunakan kekuasaan prerogatif dengan cara yang bertentangan dengan legislasi yang ada, tetapi juga sepenuhnya menolak kekuasaan pemerintah Inggris untuk mengubah secara sepihak isi hukum domestik, terlepas dari apakah parlemen telah membuat undang-undang di area tersebut atau tidak. Dorongan asas tersebut, dengan kata lain, hanya sebagian tentang menjaga supremasi legislasi parlemen. Ini juga tentang membatasi, dan mempromosikan tanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Dampaknya adalah mengharuskan pemerintah Inggris, jika ingin mengubah isi hukum dalam negeri, untuk melakukan salah satu dari dua hal. Pertama, berupaya memberlakukan undang-undang primer melalui proses legislatif parlementer. Kedua, memperoleh mandat yang jelas dari parlemen untuk membuat undang-undang yang didelegasikan. 70 Kekuasaan prerogatif tidak dapat diandalkan sebagai jalur ketiga. 71
Prinsip kedua secara langsung mengalir dari asas tidak adanya eksekutif yang membuat undang-undang. Kekuasaan hukum untuk menandatangani dan meratifikasi perjanjian terus ada sebagai pengulangan kekuasaan prerogatif, yang diberikan oleh eksekutif. 72 Oleh karena itu, tindakan ratifikasi perjanjian semata tidak dapat dianggap telah mengubah isi hukum domestik. Jika berpendapat sebaliknya, berarti memberikan kekuasaan kepada eksekutif untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh asas pertama.
Prinsip-prinsip ini memberikan batasan penting pada pengaruh yang dapat diberikan perjanjian terhadap penalaran hukum pengadilan domestik. Pertama-tama, ini berarti bahwa pengadilan tidak dapat menggunakan ketentuan perjanjian sebagai standar hukum yang berdiri sendiri dan mengikat. Sering dikatakan bahwa ratifikasi perjanjian ‘tidak memaksakan tugas hukum [domestik] pada Eksekutif [dan] juga tidak memberikan hak kepada individu’. 73 Namun, jika hanya berfokus pada ‘hak dan kewajiban’, berisiko mengaburkan poin yang lebih luas. Yaitu, bahwa ratifikasi perjanjian tidak dengan sendirinya memperkenalkan standar hukum apa pun – pemberian hak, pengenaan tugas, atau lainnya 74 – ke dalam hukum domestik. Dengan demikian, ketentuan perjanjian juga tidak dapat diandalkan sebagai pembelaan terhadap tindakan perdata 75 atau pidana 76 , bahwa pelanggaran hukum perjanjian itu sendiri bukanlah dasar yang diakui untuk peninjauan kembali yudisial 77 dan bahwa pengadilan tidak akan menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat pernyataan tentang pertanyaan hukum abstrak yang berkaitan dengan perjanjian. 78
Perlu dicatat bahwa prinsip-prinsip ini telah menjadi subjek kritik yang sering dilakukan oleh para akademisi, 79 dan terkadang hakim, 80 yang menyesalkan ketidakmampuan pengadilan untuk memanfaatkan perjanjian secara lebih langsung. Namun, prinsip-prinsip ini didukung oleh serangkaian keputusan pengadilan yang kuat dan terus bertambah, termasuk dari tingkat tertinggi. 81
Kembali ke RIPIT, mungkin, dengan tepat, ditanyakan apakah dan bagaimana kinerjanya dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang baru saja diidentifikasi. Dampak dari prinsip-prinsip ini adalah untuk melarang pengadilan menerapkan perjanjian, seperti ECAT, seolah-olah itu adalah standar hukum domestik dalam proses hukum. Namun, RIPIT, berdasarkan sifatnya, memberdayakan pengadilan untuk meninjau pedoman kebijakan untuk kepatuhannya terhadap suatu perjanjian. Perjanjian itu, setidaknya pada pandangan pertama, mungkin tampak digunakan sebagai dasar hukum peninjauan: hal yang dilarang oleh prinsip-prinsip konstitusional yang baru saja diuraikan. Bagian-bagian berikut menawarkan tanggapan tiga bagian yang terperinci terhadap keberatan ini. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan mengapa, terlepas dari penampilan pertama, munculnya RIPIT konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diidentifikasi di atas.
PRINSIP TANPA PEMBUATAN HUKUM EKSEKUTIF TIDAK BERARTI PERJANJIAN TIDAK RELEVAN SECARA MUTLAK
Poin penting awal adalah bahwa asas tidak adanya pembuatan hukum oleh eksekutif yang diartikulasikan dalam bagian sebelumnya tidak berarti bahwa pengadilan harus selalu menganggap perjanjian yang tidak berbadan hukum sebagai tidak relevan secara hukum. Seperti yang dikatakan Lord Oliver dalam kasus utama JH Rayner (Mincing Lane) Ltd v Department of Trade and Industry (International Tin Council) , asas-asas ini ‘tidak melibatkan sebagai akibat wajar bahwa pengadilan tidak boleh melihat atau menafsirkan suatu perjanjian’. 82 Sebaliknya, seperti yang telah dicatat oleh beberapa hakim dalam tulisan-tulisan ekstrayudisial, perjanjian yang tidak berbadan hukum, serta bentuk-bentuk hukum internasional lainnya, kini sering kali, dan mungkin semakin, memiliki relevansi hukum utama terhadap proses hukum domestik. 83
Dalam kasus perjanjian, relevansi hukum perjanjian dapat, dan sering kali, muncul karena sangat mungkin, memang bukan hal yang aneh, bagi standar hukum domestik untuk mengharuskan pengadilan terlibat dalam suatu perjanjian dengan cara tertentu. Hal ini sering dijelaskan, meminjam bahasa yang dikembangkan oleh Sales dan Clement, 84 sebagai hukum domestik yang menciptakan ‘pijakan’ hukum untuk perjanjian. 85 Sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung Inggris dalam Law Debenture Trust Corporation Plc v Ukraine , situasi dapat dan memang muncul ketika ‘perlu untuk memutuskan masalah hukum internasional guna menentukan masalah hukum domestik.’ 86
Yurisprudensi peninjauan kembali saja memberikan banyak contoh ‘pijakan’ hukum semacam itu untuk perjanjian. Memang, sebagian besar dasar peninjauan kembali yang ditetapkan dapat mengidentifikasi situasi di mana dasar tersebut mengharuskan atau mungkin mengharuskan pengadilan peninjau untuk terlibat dengan suatu perjanjian. Yang paling jelas, undang-undang seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998 (HRA 1998) 87 dan Undang-Undang Banding Suaka dan Imigrasi 1993 88 menempatkan otoritas publik di bawah kewajiban yang luas untuk mematuhi ketentuan perjanjian. Undang-undang juga dapat membuat ketentuan perjanjian relevan secara hukum dengan cara yang kurang langsung. Ambil contoh Undang-Undang Hak Asasi Manusia: bagian 2 HRA 1998 mengharuskan pengadilan untuk ‘memperhitungkan’ putusan Pengadilan Strasbourg. Pengadilan ini, pada gilirannya, telah menjelaskan bahwa perjanjian internasional selain Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) relevan secara hukum dengan interpretasi yang terakhir. 89 Dampak kolektif dari asas-asas hukum ini adalah bahwa HRA tidak hanya ‘mengintegrasikan’ ECHR, tetapi juga membuka jalur hukum penting yang melaluinya ketentuan-ketentuan perjanjian yang tidak tergabung dalam legislatif, seperti ECAT, 90 memberikan pengaruh signifikan terhadap penafsiran domestik atas hak-hak Konvensi. 91
Akan tetapi, bukan hanya standar legislatif yang dapat membuat perjanjian relevan secara hukum dalam proses peninjauan kembali yudisial. Penerapan dasar hukum umum untuk peninjauan kembali juga dapat mengharuskan pengadilan untuk terlibat dengan perjanjian yang tidak tergabung dalam undang-undang. 92 Persyaratan untuk mempertimbangkan hal-hal yang relevan, misalnya, dapat mengharuskan pengadilan yang meninjau untuk menentukan, sesuai dengan prinsip hukum umum, 93 apakah ketentuan perjanjian itu ‘sangat material’ terhadap keputusan yang sedang diambil sehingga pembuat keputusan seharusnya mempertimbangkannya. 94 Doktrin harapan yang sah dapat mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan apakah otoritas publik telah menawarkan representasi yang cukup jelas, 95 atau terlibat dalam praktik yang cukup konsisten 96 yang menunjukkan bahwa suatu perjanjian akan dipatuhi 97 dan, jika demikian, apakah ada pembenaran yang sah untuk penyimpangan. Dalam menerapkan asas keadilan prosedural dalam Thomas v Baptiste , 98 dalam putusan yang disampaikan oleh Lord Millett, Dewan Penasihat mempertimbangkan apakah pemerintah Trinidad dan Tobago harus diminta untuk menunda pelaksanaan hukuman mati, sambil menunggu penyelesaian petisi pemohon berdasarkan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Terakhir, asas yang mengharuskan otoritas publik untuk memberikan alasan yang sah secara hukum atas suatu keputusan 99 dapat mengharuskan pengadilan untuk mempertimbangkan apakah pertanyaan mengenai penerapan suatu perjanjian merupakan ‘isu kontroversial penting yang utama’ dalam suatu sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan yang karenanya harus ditangani oleh pembuat keputusan. 100
Para sarjana dan hakim kadang-kadang mencoba, tampaknya secara menyeluruh, untuk membuat daftar keadaan di mana hukum domestik menyediakan ‘pijakan’ bagi perjanjian. Dalam SG , misalnya, Lord Kerr menyatakan bahwa: ‘Meskipun larangan yang tampaknya menyeluruh atas penggunaan perjanjian internasional yang tidak berbadan hukum oleh pengadilan untuk mengakui hak-hak pada bidang hukum domestik, ada tiga kemungkinan cara yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan di mana perjanjian tersebut dapat berdampak pada hukum nasional – (i) sebagai bantuan untuk penafsiran undang-undang, (ii) sebagai bantuan untuk pengembangan hukum umum dan (iii) sebagai dasar untuk harapan yang sah.’ 101
Namun, kurangnya konsistensi antara isi daftar yang ditawarkan sangat mencolok. Dengan demikian, daftar tiga item Lord Kerr dalam SG (bantuan untuk konstruksi undang-undang, bantuan untuk pengembangan hukum umum, harapan yang sah) berbeda dengan daftar Lord Oliver dalam International Tin Council (bantuan untuk konstruksi undang-undang, penggabungan kontrak, latar belakang faktual untuk suatu sengketa). 102 Pengadilan yang berbeda memiliki daftar dengan item yang lebih sedikit 103 dan lebih banyak 104. Hal ini mencerminkan, baik, berbagai keadaan di mana standar hukum domestik mungkin memerlukan keterlibatan yudisial dengan perjanjian dan sifat bidang hukum ini yang terus berkembang. 105
Namun, yang menyatukan semua contoh di atas adalah bahwa penerapan standar hukum domestik – baik yang berasal dari undang-undang maupun hukum umum – menciptakan situasi di mana pengadilan harus terlibat secara hukum dengan suatu perjanjian. Tanpa melakukannya, pengadilan tidak dapat menerapkan standar tersebut secara berarti. Namun, jika tidak ada pijakan seperti itu, prinsip-prinsip konstitusional yang dibahas di bagian sebelumnya mengharuskan pengadilan untuk menganggap suatu perjanjian tidak relevan secara hukum. Banyak kasus utama mengenai (tidak)relevansinya perjanjian secara hukum telah menyangkut skenario semacam ini. Dalam International Tin Council 106 sendiri, misalnya, House of Lords menyimpulkan bahwa kepribadian hukum Dewan tersebut berasal dari undang-undang Inggris. Oleh karena itu, tidak perlu bagi pengadilan domestik untuk bergantung, seperti yang didesak oleh penggugat, pada aturan hukum Inggris bahwa tanggung jawab badan hukum asing harus ditentukan oleh hukum yang berlaku di tempat pendiriannya untuk melakukan penyelidikan apakah perjanjian yang membentuk International Tin Council mengizinkan anggotanya untuk dituntut. 107 Karena aturan hukum Inggris tersebut tidak dapat diterapkan, perjanjian tersebut tidak relevan sebagai masalah hukum domestik.
Contoh lain adalah kasus penting terkini R (SC) v Secretary of State for Work and Pensions . 108 Mahkamah Agung Inggris menyimpulkan bahwa pengadilan peninjau tidak perlu memutuskan apakah pembuat keputusan telah mematuhi Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak Anak (UNCRC), sebuah perjanjian yang tidak tergabung dalam legislatif, ketika menerapkan prinsip proporsionalitas dalam tantangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 109 Kesimpulan ini dapat dijelaskan atas dasar bahwa, sebagai masalah prinsip yang mapan, fokus penyelidikan proporsionalitas adalah substansi pembenaran yang dimaksudkan oleh otoritas publik atas pelanggaran hak: 110 proporsionalitas tidak menempatkan otoritas publik itu sendiri di bawah kewajiban hukum untuk mengikuti proses tertentu dalam mencapai keputusan awalnya. 111 Penetapan, dengan satu atau lain cara, mengenai apakah pembuat keputusan dalam proses pengambilan keputusannya sendiri telah memperlakukan kepentingan terbaik anak sebagai ‘utama’, 112 karenanya, tidak dianggap oleh Mahkamah Agung Inggris untuk membantu pengadilan dalam menangani masalah hukum domestik utama yang muncul dalam kasus tersebut. Sederhananya, menurut pandangan pengadilan, tidaklah perlu atau sangat membantu untuk menerapkan UNCRC guna menerapkan standar hukum domestik.
Bahasa Indonesia: Kembali sekarang ke RIPIT, pertanyaan penting karenanya muncul. Yaitu, ke dalam kotak mana dari dua kotak tersebut yurisprudensi RIPIT jatuh. Pilihan pertama adalah bahwa pengadilan yang terlibat dalam RIPIT sedang meninjau pedoman kebijakan secara langsung terhadap ketentuan perjanjian yang tidak tergabung dalam legislatif. Jika demikian, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa itu adalah iterasi peninjauan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dibahas dalam bagian sebelumnya, dan tidak konsisten dengan otoritas yang telah diputuskan termasuk International Tin Council dan SC . Pilihan kedua, bagaimanapun, adalah bahwa pengadilan yang terlibat dalam RIPIT sedang meninjau terhadap standar hukum domestik, yang penerapannya memerlukan keterlibatan dengan suatu perjanjian. Bagian selanjutnya bertujuan untuk menunjukkan mengapa RIPIT jatuh ke dalam kotak kedua ini.
RIPIT SEBAGAI APLIKASI STANDAR HUKUM ADMINISTRASI DOMESTIK
Pembahasan pada bagian kedua di atas secara singkat menyinggung poin bahwa pengadilan yang secara eksplisit telah menangani dasar hukum RIPIT hingga saat ini tidak mengabaikan keberatan konstitusional yang sedang dipertimbangkan. Sebaliknya, dalam dua kasus – Galdikas 113 dan KTT 114 – hakim telah memberikan tanggapan langsung. Tanggapan tersebut mencakup penggambaran RIPIT sebagai penerapan prinsip hukum administrasi domestik yang mapan. Yaitu, prinsip Mandalia . Prinsip inilah yang dikatakan memberikan ‘pijakan’ hukum yang melegitimasi keterlibatan peradilan dengan perjanjian seperti ECAT.
Bagian ini mengemukakan dua argumen. Yang pertama menjelaskan mengapa kasus RIPIT tidak dapat dipahami dengan baik sebagai penerapan prinsip Mandalia dan mengapa pembelaan pengadilan terhadap RIPIT hingga saat ini tidak memuaskan. Yang kedua berpendapat bahwa, bagaimanapun, adalah mungkin untuk menemukan landasan doktrinal yang lebih aman untuk RIPIT. RIPIT dapat dipahami dengan baik sebagai penerapan prinsip ABCIFER , yang menurutnya suatu kebijakan tidak rasional jika kriterianya tidak mampu mewujudkan tujuan yang menjadi dasar kebijakan tersebut diumumkan.
RIPIT sebagai penerapan prinsip Mandalia ?
Upaya pengadilan untuk mengkarakterisasi RIPIT sebagai penerapan hukum domestik hingga saat ini berpusat pada prinsip penting hukum administrasi yang dikonkretkan oleh Mahkamah Agung Inggris dalam Mandalia . 115 Mandalia menyangkut penolakan perpanjangan visa. Kementerian Dalam Negeri gagal menerapkan surat edaran kebijakan yang mengarahkan pekerja kasus untuk menunjukkan fleksibilitas administratif. Mahkamah Agung Inggris menyimpulkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertindak melawan hukum dan, dengan melakukannya, mengklarifikasi bahwa sekarang ada prinsip hukum administrasi yang ‘berdiri sendiri’ yang mengharuskan ‘pembuat keputusan [untuk] mengikuti kebijakannya yang dipublikasikan … kecuali ada alasan yang kuat untuk tidak melakukannya. ‘
Bahasa Indonesia: Dalam Galdikas , Sir Stephen Silber, dalam penalaran yang kemudian didukung oleh Pengadilan Banding dalam EOG/KTT , berusaha menjelaskan RIPIT sebagai penerapan prinsip ini. Di latar belakang pedoman NRM, dikatakan, Menteri Dalam Negeri telah mengadopsi posisi ‘kebijakan’ bahwa pedoman tersebut harus sesuai dengan ECAT. Prinsip Mandalia dengan demikian dikatakan menempatkan Menteri Dalam Negeri di bawah tugas hukum praduga, ketika menyusun pedoman NRM, untuk memastikan ketentuannya mencerminkan dengan tepat ketentuan perjanjian. Argumen ini merupakan upaya yang jelas untuk menyelamatkan RIPIT dari keberatan konstitusional yang dipertimbangkan dalam artikel ini. Argumen ini berusaha mengkarakterisasi RIPIT sebagai penerapan standar hukum domestik.
Meskipun telah mendapatkan dukungan dari pengadilan, penjelasan ini gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang RIPIT setidaknya karena tiga alasan yang terkait. Pertama, peninjauan berdasarkan Mandalia dan RIPIT tidaklah dapat dianalogikan secara dekat. Keduanya terjadi dalam jenis kasus yang sangat berbeda. Subjek yang ditentang dalam kasus Mandalia adalah keputusan khusus , yang ‘ditargetkan’ 118 pada individu atau organisasi tertentu, seperti penolakan untuk memperpanjang visa atau memanggil kembali seseorang ke rumah sakit. 119 Kesalahan hukum terjadi ketika keputusan khusus tersebut menyimpang dari standar kebijakan umum yang telah diumumkan untuk memandu pengambilan keputusan. Sebaliknya, kasus RIPIT memiliki fokus yang sangat berbeda. Keduanya memerlukan peninjauan atas isi dokumen kebijakan itu sendiri terhadap tujuan yang telah diumumkan.
Kedua, dan terkait, ‘kebijakan’ yang menjadi dasar peninjauan keputusan relevan berbeda dalam kedua jenis kasus tersebut. Mandalia berlaku jika otoritas publik mengumumkan dokumen kebijakan yang ‘dilihat, secara objektif, berfungsi sebagai instrumen preskriptif’ 120 untuk memandu pengambilan keputusan. Alasan dalam Galdikas menggunakan bahasa ‘kebijakan’ dengan cara yang sangat berbeda. ‘Kebijakan’ yang seharusnya menjadi dasar tindakan konsisten Menteri Dalam Negeri adalah tujuan kebijakan yang luas untuk mengamankan kepatuhan, melalui pembuatan dokumen kebijakan, dengan kewajiban perjanjian internasional Inggris.
Ketiga dan terakhir, hasil dari semua ini adalah bahwa menjelaskan RIPIT dengan merujuk pada Mandalia melibatkan, paling tidak, perluasan prinsip yang cukup besar. Namun, hal ini tidak sesuai dengan pola umum dalam yurisprudensi pasca- Mandalia , yang mengarah pada penyempitan penerapan prinsip. Contoh terpenting adalah keputusan Pengadilan Banding dalam R (Good Law Project) v Prime Minister 121 ( Good Law Project ). Pengadilan dengan suara bulat memutuskan bahwa prinsip Mandalia tidak berlaku untuk sekelompok kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan platform non-resmi, termasuk WhatsApp, sebagai moda komunikasi menteri. Putusan tersebut membedakan antara kebijakan yang ‘secara langsung memengaruhi publik’, 122 yang dikatakan berlaku untuk Mandalia , dan kebijakan yang hanya ‘mengatur administrasi internal departemen Pemerintah … dan tidak terkait dengan kasus individu atau hak individu’, 123 yang dianggap tidak berlaku untuk Mandalia . Alasan pengadilan dalam Good Law Project telah menjadi sasaran kritik akademis yang meyakinkan. Yang paling menonjol, Tom Hickman dan Thomas Poole 124 mengkritik pembedaan antara kebijakan eksternal dan internal karena tidak konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya 125 dan mengabaikan berbagai nilai hukum yang dipromosikan oleh prinsip umum yang mengharuskan kepatuhan praduga terhadap kebijakan. 126 Kritik Hickman dan Poole meyakinkan. Namun, poin penting untuk tujuan saat ini adalah bahwa Good Law Project menggambarkan tren umum dalam yurisprudensi yang membatasi prinsip Mandalia hanya pada jenis dokumen kebijakan tertentu. Ini adalah perkembangan yang tidak sesuai dengan penggunaan prinsip yang jauh lebih luas yang disyaratkan oleh Galdikas . 127
RIPIT sebagai penerapan prinsip ABCIFER
Akan tetapi, tidak berarti bahwa, karena RIPIT tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan sebagai penerapan prinsip Mandalia , maka hal itu harus dianggap melanggar prinsip konstitusional. Sebaliknya, dalam menjalankan RIPIT, pengadilan dapat dianggap menerapkan standar lain yang mapan untuk peninjauan kembali yudisial. Yaitu, agar rasional, dan karenanya sah, suatu kebijakan harus secara wajar mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkannya. Standar ini akan disebut sebagai ‘ prinsip ABCIFER ‘ setelah kasus utama di mana ia diartikulasikan. 128
Ini adalah asas yang mapan dalam peninjauan kembali yudisial di Inggris dan Wales bahwa, agar sah, suatu keputusan haruslah rasional. 129 Atau, dengan kata lain, irasionalitas adalah dasar hukum domestik yang diakui secara universal untuk peninjauan kembali yudisial. Makna dan hakikat yang tepat dari peninjauan kewajaran, serta hubungannya dengan doktrin proporsionalitas, tentu saja, merupakan subjek perdebatan ilmiah yang kaya. 130 Namun , satu hal yang diterima secara umum adalah bahwa ada berbagai ‘kategori’ 132 atau ‘indicia’ 133 yang berbeda dari ketidakwajaran. Dengan kata lain, yang termasuk dalam judul ‘irasionalitas’, adalah sub-asas lebih lanjut yang mengartikulasikan dalam istilah yang lebih tepat bagaimana seorang pembuat keputusan dapat gagal bertindak secara rasional.
Salah satu prinsip tersebut muncul dari kasus ABCIFER . Pemohon menentang skema kompensasi ex gratia untuk warga sipil Inggris yang ditahan oleh otoritas Jepang selama perang dunia kedua. Skema tersebut mengharuskan pemohon, atau orang tua atau kakek-nenek, lahir di Inggris. Pemohon berpendapat bahwa kriteria ini tidak rasional karena tidak cukup terkait dengan tujuan utama skema tersebut. Pengadilan Banding menolak tantangan tersebut atas dasar bahwa tujuan skema tersebut adalah untuk memastikan pemohon memiliki ‘hubungan yang kuat’ dengan Inggris, dan kriteria tempat lahir cukup terkait dengan tujuan ini. 134 Namun, yang terpenting, pengadilan menerima bahwa ‘sama seperti dalam memenuhi persyaratan proporsionalitas, demikian pula dalam memenuhi uji Wednesbury [tentang irasionalitas], tindakan yang dirancang untuk memajukan tujuan tersebut harus secara rasional terkait dengannya.’ 135 Dengan kata lain, salah satu cara pembuat kebijakan dapat gagal memenuhi persyaratan hukum rasionalitas adalah melalui penerapan kriteria kebijakan yang jelas-jelas tidak sesuai untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut diumumkan.
Seperti yang diilustrasikan ABCIFER , ambang batas hukumnya relatif tinggi. Seperti yang dikatakan Lord Dyson, ‘kriteria diharuskan untuk melakukan tidak lebih dari sekadar mendefinisikan secara rasional cara’ tujuan kebijakan akan dikejar. 136 Oleh karena itu, pemohon menanggung ‘beban untuk menunjukkan bahwa [kriteria] … tidak konsisten dengan tujuan skema’. 137 Namun, ada kasus-kasus di mana beban itu telah dilepaskan. 138 Dalam R (Limbu) v Secretary of State for the Home Department , 139 misalnya, ketentuan kebijakan tentang pemberian izin masuk kepada veteran Gurkha dianggap ‘secara tidak rasional mengecualikan materi … konteks dan tujuan kebijakan yang dinyatakan menunjukkan seharusnya disertakan … [atau] sangat ambigu’ 140 sehingga mereka tidak mampu mewujudkan tujuan kebijakan. Baru-baru ini dalam kasus R (Bailey) v Secretary of State for Justice ( Bailey ) perubahan terhadap aturan Dewan Pembebasan Bersyarat dianggap tidak rasional karena tidak mampu mewujudkan tujuan (yang tidak pantas) Menteri untuk ‘menekan … bukti pendapat yang saat ini tersedia untuk Dewan [Pembebasan Bersyarat]’. 142
Prinsip ABCIFER ini mampu memberikan landasan doktrinal yang lebih aman bagi RIPIT daripada prinsip Mandalia . Inti dari prinsip ABCIFER adalah persyaratan bagi para penyusun kebijakan untuk mengadopsi kriteria yang secara wajar mampu mewujudkan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, pengadilan yang menerapkan standar ini diharuskan untuk menanyakan apakah terdapat ketidaksesuaian mendasar antara tujuan kebijakan tersebut diumumkan dan ketentuan yang ditetapkan. Dalam banyak kasus hukum yang diputuskan hingga saat ini – termasuk ABCIFER dan Limbu – kebijakan yang sedang ditinjau diadopsi untuk tujuan selain penerapan perjanjian. Namun, kasus hukum RIPIT dapat dijelaskan dengan baik sebagai penerapan baru prinsip ini pada contoh khusus dokumen kebijakan yang diadopsi dengan tujuan mengamankan kepatuhan perjanjian. Dalam kasus RIPIT, sama seperti dalam ABCIFER , dengan kata lain, pengadilan menentukan apakah penyusun kebijakan telah mematuhi kewajiban hukum domestiknya untuk bertindak secara rasional, khususnya dengan menyusun kebijakan dalam ketentuan yang mampu mewujudkan tujuan yang diumumkan.
Dengan kata lain, prinsip ABCIFER- lah yang menyediakan ‘pijakan’ hukum yang melegitimasi keterlibatan yudisial dengan sebuah perjanjian dalam kasus RIPIT. Dalam kasus RIPIT, pengadilan yang meninjau tidak secara langsung menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian seolah-olah itu adalah standar hukum domestik. Pengadilan juga tidak memperlakukan pedoman kebijakan atau maksud pembuat kebijakan sebagai ‘pijakan’ hukum yang membenarkan keterlibatan dengan sebuah perjanjian. Pengadilan memberlakukan prinsip hukum administrasi domestik yang mapan, dalam konteks kebijakan tertentu yang diumumkan untuk tujuan khusus mengamankan kepatuhan perjanjian. Untuk menerapkan prinsip ini, dalam konteks jenis ini, sering kali ‘diperlukan’ 143 untuk terlibat dengan ketentuan-ketentuan perjanjian dan menanyakan apakah perancang telah mengadopsi interpretasi yang tidak tepat darinya. Namun, dengan melakukannya, pengadilan tidak menggunakan perjanjian itu sebagai standar hukum domestik itu sendiri. Pengadilan juga tidak memperlakukan eksekutif seolah-olah memiliki kewenangan untuk mengubah isi hukum domestik secara sepihak. Bukan tindakan meratifikasi perjanjian atau mengumumkan kebijakan yang menjadi dasar hukum RIPIT. Prinsip ABCIFER- lah yang, dalam konteks kebijakan pelaksanaan perjanjian, menjadikan hukum perjanjian relevan secara sentral dan tak terelakkan terhadap sengketa hukum domestik yang sedang dihadapi.
HUKUM UMUM DAN PERKEMBANGAN BERTAMBAHAN ‘PIJAKAN’ HUKUM BAGI PERJANJIAN
Dalam menanggapi keberatan konstitusional terhadap RIPIT yang diuraikan di bagian kedua, artikel sejauh ini telah menunjukkan dua hal. Pertama, ketidakmampuan eksekutif untuk mengubah hukum domestik secara sepihak tidak berarti perjanjian menjadi tidak relevan secara hukum: penerapan standar hukum domestik dapat dan memang memerlukan keterlibatan yudisial dengan perjanjian. Kedua, pengadilan yang terlibat dalam RIPIT dapat dilihat sebagai penerapan prinsip hukum administrasi domestik yang mapan, prinsip ABCIFER . Bagian ini memberikan poin lebih lanjut untuk membela RIPIT. Yaitu, tidak ada yang tidak biasa atau bermasalah tentang hukum umum , berbeda dengan standar legislatif, yang menyediakan ‘pijakan’ untuk perjanjian dalam hukum Inggris dan Wales.
Hal ini bukanlah hal baru dan telah dikemukakan sebelumnya dalam literatur akademis. Memang, ini adalah tema yang menjadi inti dari makalah penting David Dyzenhaus, Murray Hunt, dan Michael Taggart tentang ‘internasionalisasi’ hukum administrasi domestik, 144 yang dibahas secara lebih rinci di bawah ini. Namun, pada saat yang sama, kini ada kecenderungan umum yang mencolok di pihak hakim dan akademisi, ketika berupaya menjelaskan hubungan antara perjanjian, hukum Inggris, dan pengadilan domestik, untuk menekankan perlunya intervensi legislatif jika suatu perjanjian ingin memiliki relevansi hukum. Dalam R (FDA) v Minister for Cabinet Office , misalnya, Pengadilan Tinggi menjelaskan bahwa ‘di Inggris Raya … hukum [perjanjian] internasional bukan bagian dari hukum domestik kecuali jika telah dimasukkan ke dalam hukum domestik oleh atau berdasarkan Undang-Undang Parlemen ‘. 145 Demikian pula, Pengadilan Banding Irlandia Utara baru-baru ini menyatakan bahwa ‘hasil dari sistem dualis kita’ adalah bahwa ‘perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum domestik kita hanya jika undang-undang disahkan untuk tujuan tersebut’. 146
Namun, penekanan yang kuat pada kebutuhan undang-undang untuk memberikan relevansi hukum pada perjanjian tidak sesuai dengan, atau setidaknya berisiko mengaburkan, beberapa fitur penting dari yurisprudensi. Meskipun memang benar bahwa banyak contoh standar hukum yang paling signifikan yang mengharuskan keterlibatan yudisial dengan perjanjian adalah undang-undang, standar hukum umum juga dapat dan telah membuat perjanjian relevan secara hukum dalam berbagai cara yang berbeda. Beberapa contoh ini, diambil dari konteks khusus peninjauan yudisial, dibahas di atas. Untuk kembali ke yang pertama , merupakan persyaratan umum hukum umum bahwa pembuat keputusan administratif memperhatikan pertimbangan yang ‘begitu “jelas material” sehingga [akan] tidak rasional untuk tidak [mempertimbangkannya].’ Prinsip ini biasanya diterapkan pada pertimbangan – keterbatasan sumber daya, janji manfaat masyarakat dalam perselisihan perencanaan, dll. – selain perjanjian. Akan tetapi, skenario dapat muncul ketika ketentuan-ketentuan perjanjian begitu jelas terkait dengan isi suatu keputusan sehingga ambang batas materialitas yang jelas terpenuhi. Elliott-Smith adalah contoh yang baik . 152 Kasus tersebut menyangkut tantangan terhadap skema perdagangan emisi karbon baru. Dove J menerima bahwa Perjanjian Paris, perjanjian internasional terpenting yang tidak berbadan hukum 153 tentang perubahan iklim, 154 ‘jelas material’ bagi pembentukan skema tersebut. 155 Oleh karena itu, Sekretaris Negara secara hukum diharuskan untuk memperhatikannya. Yang terpenting, itu adalah standar hukum umum – yaitu, tugas hukum untuk memperhatikan semua hal yang ‘jelas material’ – yang membuat perjanjian tersebut relevan secara hukum dalam kasus ini, bukan ketentuan dalam undang-undang.
Contoh lain adalah R v Secretary of State for the Home Department, ex p Launder 156 ( Launder ) dan R v Director of Public Prosecutions, ex p Kebilene ( Kebilene ). 157 Kasus-kasus ini terkenal karena menetapkan bahwa pembuat keputusan yang secara sukarela mempertimbangkan sebuah perjanjian harus bertindak berdasarkan pemahaman yang tepat tentang perjanjian tersebut. Prinsip ini telah menjadi subjek kritik 158 dan masih ada ketidakpastian tentang pendekatan yudisial yang seharusnya diambil untuk menafsirkan perjanjian ketika digunakan. 159 Namun, yang penting, perkembangan tersebut merupakan contoh pijakan yang mapan yang melaluinya perjanjian menjadi relevan dalam penyelesaian sengketa domestik 160 yang merupakan hasil dari hukum umum , bukan standar legislatif.
Bahasa Indonesia: Poin penting lebih lanjut yang berisiko dikaburkan oleh penekanan berlebihan pada kebutuhan untuk penggabungan legislatif adalah bahwa hukum umum juga mampu berkembang dengan cara yang mengharuskan pengadilan untuk terlibat dengan perjanjian dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Prinsip yang ditetapkan oleh Launder dan Kebilene , sekali lagi, menawarkan contoh penting. Yang lain adalah Kuwait Airways Corp v Iraqi Airways Co 161 ( Kuwait Airways ). House of Lords dalam kasus ini memperluas prinsip hukum Inggris yang ada yang memberdayakan pengadilan untuk menolak mengakui hukum asing yang secara terang-terangan melanggar hak-hak fundamental, 162 untuk mencakup skenario di mana hukum asing melanggar hukum internasional. Memang, ada dukungan kuat dalam kedua kasus hukum 163 dan komentar 164 bahwa memastikan kepatuhan yang lebih dekat dengan hukum internasional, termasuk perjanjian, memberikan alasan positif untuk mengembangkan hukum umum. 165 Dalam Kuwait Airways Lord Nicholls menjelaskan bahwa ‘pengadilan negara ini harus … [umumnya berusaha untuk memberikan] efek pada aturan hukum internasional yang ditetapkan dengan jelas’ 166 melalui evolusi hukum umum.
Memang benar bahwa, khususnya dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan telah berulang kali menekankan batasan penting pada sejauh mana pengadilan dapat mengembangkan hukum umum untuk menciptakan ‘pijakan’ baru bagi perjanjian. Yaitu, cara ‘bertahap’ di mana hukum umum berkembang. Dalam R (Elgizouli) v Secretary of State for the Home Department , Lord Reed menjelaskan prinsip ini berasal dari dua pertimbangan. Pertama, bahwa keputusan pengadilan ‘biasanya melihat ke belakang dalam arti bahwa mereka memutuskan hukum apa yang relevan pada saat itu’ yang berarti bahwa ‘[p]enuntuhan untuk menjaga kepastian hukum, pengembangan hukum umum oleh pengadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mapan, membangunnya secara bertahap daripada membuat perubahan yang lebih dramatis’. 167 Kedua, ‘keterbatasan prosedural dan kelembagaan yang membatasi kemampuan litigasi di depan pengadilan untuk bertindak sebagai mesin reformasi hukum.’ 168 Sifat ‘bertahap’ dari hukum umum telah menjadi tema yang berulang dalam penalaran hukum Mahkamah Agung Inggris dalam beberapa tahun terakhir, secara umum. 169 Hal ini juga jelas memiliki pengaruh yang membatasi dalam kasus-kasus di mana pengadilan diundang untuk mengembangkan ‘pijakan’ hukum umum baru untuk perjanjian dalam sejumlah cara penting.
Satu batasan penting adalah bahwa seorang penggugat yang berusaha membujuk pengadilan untuk mengembangkan hukum umum sehingga menciptakan ‘pijakan’ baru untuk sebuah perjanjian umumnya hanya akan berhasil jika mereka mampu menunjukkan prinsip yang ada yang pengadilan mampu ‘sesuaikan secara wajar’. 170 Contoh yang baik adalah kasus baru-baru ini Law Debenture Trust v Ukraine . 171 Penggugat berusaha untuk menegakkan kontrak terhadap negara Ukraina, yang terakhir berpendapat telah dibuat sebagai akibat dari ‘tekanan ekonomi dan politik yang besar, tidak sah dan tidak sah’ 172 oleh Rusia. Antara lain, Ukraina berusaha untuk berpendapat bahwa penolakan untuk memenuhi kontrak dapat dibenarkan sebagai tindakan balasan yang proporsional. Penasihat berusaha membujuk Mahkamah Agung Inggris untuk mengembangkan hukum umum untuk memungkinkan Ukraina mengandalkan prinsip hukum kebiasaan internasional ini sebagai pembelaan terhadap klaim kontrak domestik. Mahkamah Agung Inggris menolak undangan tersebut, 173 dengan menyatakan bahwa ‘tidak ada aturan hukum umum yang berlaku yang dapat disesuaikan secara wajar oleh pengadilan untuk mencerminkan’ 174 posisi hukum internasional. Prinsip tindakan balasan adalah salah satu hukum internasional kebiasaan, bukan hukum perjanjian. Meskipun demikian, kasus tersebut menggambarkan keraguan umum pengadilan untuk mengembangkan ‘pijakan’ hukum umum baru bagi hukum internasional selain secara bertahap. 175
Batasan lain yang terkait adalah keengganan umum pengadilan untuk ‘menyesuaikan’ standar hukum umum yang ada dengan cara yang bertentangan dengan fitur-fitur yang sudah mapan dan mendasar. Sekali lagi, Law Debenture Trust v Ukraine memberikan ilustrasi yang menarik. Selain mencoba mengandalkan doktrin tindakan balasan, Ukraina juga berusaha untuk menyatakan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian di bawah tekanan. Mahkamah Agung Inggris menerima bahwa doktrin domestik yang ada tentang tekanan paksaan memungkinkan Ukraina untuk mengandalkan ancaman kekerasan fisik. Namun, mereka juga diminta untuk memperluas pembelaan hukum umum untuk memperhitungkan penggunaan tekanan ekonomi yang melanggar hukum internasional oleh Rusia sebagai bentuk tekanan yang ‘tidak sah’. Sekali lagi, pengadilan menolak undangan tersebut. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan otoritas sebelumnya yang dengan jelas ‘menolak uji penerimaan moral atau sosial yang luas sebagai batu ujian’ 176 dan sengaja mengadopsi pendekatan yang sempit terhadap tekanan ekonomi. 177
Akhirnya, pengadilan dapat menolak untuk mengembangkan pijakan hukum umum baru jika efek dari melakukannya adalah untuk secara dramatis mengubah hubungan antara parlemen, eksekutif dan pengadilan. Hal ini diilustrasikan dengan baik oleh kasus pra-HRA 1998, R v Secretary of State for the Home Department, ex p Brind . 178 Kasus tersebut menyangkut prinsip konstruksi undang-undang yang mapan yang mengharuskan pengadilan ‘dalam menafsirkan ketentuan apa pun dalam undang-undang domestik yang ambigu … [untuk] menganggap bahwa Parlemen bermaksud untuk membuat undang-undang sesuai’ dengan hukum internasional’. 179 Pemohon berusaha membujuk House of Lords untuk mengembangkan prinsip itu dengan cara yang akan ‘menganggap Parlemen’ sebagai ‘niat yang lebih umum … [yaitu,] bahwa eksekutif harus menggunakan kebijaksanaan sesuai dengan [ECHR]’. 180 Jika House of Lords menerima argumen ini, efeknya akan menempatkan eksekutif di bawah tugas hukum umum untuk bertindak secara konsisten dengan hak-hak Konvensi, dengan pengadilan yang bertindak sebagai penengah. House of Lords berpendapat bahwa perubahan hukum sebesar ini hanya boleh diperkenalkan oleh parlemen. Dalam kata-kata Lord Bridge:
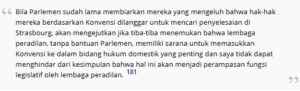
Bahasa Indonesia: Kembali lagi ke RIPIT, tiga poin kini layak dibuat, berdasarkan hal di atas. Pertama, analisis dalam bagian ini menunjukkan bahwa tidak dapat menjadi keberatan terhadap RIPIT bahwa standar hukum yang memberikan ‘pijakan’ untuk sebuah perjanjian adalah hukum umum, dan bukan standar legislatif. Kedua, juga bukan suatu keberatan untuk mengatakan bahwa RIPIT memerlukan pengakuan pijakan hukum umum baru untuk perjanjian. Seperti kasus-kasus seperti Kuwait Airways , Launder dan Kebilene menunjukkan, hukum umum sepenuhnya mampu berkembang dengan cara yang mengharuskan pengadilan untuk terlibat dengan perjanjian dengan cara-cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam hal apa pun, perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi RIPIT sepenuhnya sesuai dengan cara bertahap di mana hukum umum berkembang di area ini, jika itu dapat secara akurat digambarkan sebagai penanda ‘perkembangan’ hukum umum sama sekali. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, RIPIT paling baik dilihat sebagai penerapan prinsip peninjauan kembali yudisial domestik yang mapan, yaitu prinsip ABICFER , pada konteks spesifik suatu kebijakan yang diumumkan untuk tujuan mengamankan kepatuhan terhadap perjanjian. Dengan kata lain, kebaruan yang terkandung dalam RIPIT adalah penerapan standar yang mapan pada jenis kebijakan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, bukan dalam penciptaan standar baru.
Ketiga dan terakhir, perlu juga ditunjukkan bahwa jika RIPIT mensyaratkan, dalam beberapa hal, perluasan prinsip-prinsip hukum umum, maka itu adalah salah satu yang disambut baik yang mempromosikan setidaknya dua nilai penting. Pertama, kemanjuran. Seperti yang ditekankan Pengadilan Banding dalam EOG/KTT , prasyarat yang diperlukan untuk RIPIT adalah adanya kebijakan yang secara nyata dimaksudkan untuk mengamankan kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian. Ketidakkonsistenan antara isi kebijakan tersebut dan perjanjian yang dimaksudkan untuk dilaksanakan akan berarti, secara sederhana, bahwa kebijakan tersebut gagal mencapai tujuannya. Memang, nilai kemanjuran RIPIT dapat menjelaskan mengapa Home Office begitu sering mengandalkan konsesi Atamewan , yang secara efektif mengundang pengadilan untuk terlibat dalam RIPIT. Sederhananya, akan sering menjadi kepentingan otoritas publik untuk mengetahui apakah kebijakan mereka gagal mencapai tujuan kepatuhan perjanjian yang ingin mereka capai.
Kedua, RIPIT juga mendorong transparansi. Tanpa ketersediaan RIPIT, ada risiko otoritas publik dapat menampilkan diri mereka sebagai pihak yang mengupayakan kepatuhan perjanjian, sementara pada saat yang sama mengadopsi ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak sesuai. RIPIT memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ini. Dampaknya adalah bahwa otoritas publik yang telah menyajikan dokumen kebijakan sebagai langkah-langkah yang dirancang untuk mengamankan kepatuhan perjanjian memiliki dua pilihan: mereka dapat memastikan bahwa ketentuan-ketentuan kebijakan individual memang sesuai perjanjian, atau, jika mereka memilih untuk mengadopsi langkah-langkah yang tidak sesuai perjanjian, mereka harus melakukannya secara terbuka dengan mengklarifikasi bahwa kepatuhan perjanjian bukan lagi tujuan kebijakan.
MEREFLEKSI NOMENKLATUR: MENGAPA KITA AKAN BAIK MENJAUHI ‘DUALISME’
Artikel sejauh ini telah menyoroti munculnya RIPIT dan berusaha mempertahankannya terhadap keberatan konstitusional yang penting. Analisis yang tersisa menawarkan beberapa refleksi yang lebih luas. Tujuan dari bagian ini adalah untuk mendorong pertimbangan apakah nomenklatur yang umumnya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara perjanjian, pengadilan, dan hukum Inggris masih berguna. Fokusnya adalah pada satu istilah yang sangat berpengaruh: ‘dualisme’.
Ada baiknya untuk memulai dengan poin klarifikasi awal. Pembahasan di bawah ini menawarkan penolakan terhadap penggunaan istilah ‘dualisme’ yang berkelanjutan dalam wacana hukum publik Inggris. Namun, ini bukan bentuk penolakan ‘keras’ yang ditawarkan oleh beberapa pihak. Sejumlah komentator telah berusaha untuk berargumen bahwa istilah ‘dualisme’ harus ditinggalkan dalam arti bahwa pengadilan harus mengakui bahwa, setidaknya kadang-kadang, ratifikasi perjanjian mampu memperkenalkan standar hukum domestik yang baru. 182 Dalam sebuah artikel yang digambarkan oleh Mahkamah Agung Inggris sebagai ‘sangat radikal’ dan ‘tidak mungkin disukai oleh pengadilan’, 183 misalnya, Bharat Malkani berpendapat bahwa kodifikasi undang-undang dari Aturan Ponsonby 184 harus dilihat telah memberi wewenang kepada ‘pengadilan untuk memberikan efek [langsung] pada perjanjian hak asasi manusia tanpa perlu menunggu Parlemen untuk memberlakukan undang-undang yang mengubah.’ 185 Tantangan ‘keras’ terhadap dualisme semacam ini menghadapi kendala besar. Yaitu, semakin banyaknya kasus hukum, yang dibahas di seluruh artikel ini, yang secara konsisten menegaskan kembali bahwa ratifikasi perjanjian tidak dengan sendirinya memperkenalkan standar hukum domestik yang baru. Oleh karena itu, tantangan yang diajukan terhadap istilah ‘dualisme’ dalam artikel ini lebih lunak. Argumennya adalah, meskipun menerima bahwa ratifikasi perjanjian tidak menciptakan hukum domestik yang baru dan dapat diberlakukan, istilah tersebut tidak membantu dalam menangkap sifat hubungan yang terjerat secara hukum yang sekarang menjadi ciri perjanjian, hukum Inggris, dan pengadilan domestik.
Akan sangat membantu jika kita mulai dengan menyatakan kembali secara singkat seperti apa dasar-dasar hubungan tersebut. Seperti yang disoroti pada bagian ketiga di atas, titik awalnya adalah dua prinsip konstitusional yang mapan dan saling terkait. Pertama, bahwa eksekutif tidak memiliki kewenangan sepihak untuk mengubah isi hukum nasional. Kedua, bahwa pengadilan tidak dapat menganggap ratifikasi perjanjian, sebagai pelaksanaan kewenangan prerogatif, sebagai pengenalan standar baru yang berdiri sendiri ke dalam hukum nasional. Seperti yang ditekankan pada bagian-bagian selanjutnya dari artikel ini, tidak ada dalam prinsip-prinsip ini yang mencegah badan pembuat hukum nasional mengembangkan dan menerapkan standar hukum dengan cara yang membuat perjanjian relevan dalam berbagai cara. Dengan demikian, Parlemen berhak sepenuhnya, dan sering kali melakukannya, ‘memasukkan’ perjanjian melalui berbagai teknik penyusunan undang-undang. Yang terpenting, pengadilan juga memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan dan menerapkan standar hukum umum dengan cara yang mengharuskan keterlibatan hukum dengan perjanjian yang tidak dimasukkan dalam undang-undang.
Memang, beberapa hakim dan komentator telah melihat dengan jelas pengembangan hukum umum untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dengan hukum perjanjian yang tidak berbadan hukum sebagai sesuatu yang harus secara aktif dikejar oleh pengadilan. 186 Dalam sebuah makalah penting yang diterbitkan pada tahun 2001, misalnya, Dyzenhaus, Hunt, dan Taggart mencirikan pengadilan dalam sistem hukum umum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melihat hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia internasional, sebagai bagian dari proses yang sedang berlangsung untuk ‘memperbarui katalog nilai-nilai yang menjadi subjek hukum umum bagi negara administratif.’ 187 Bagi para penulis ini, dengan kata lain, posisi konstitusional pengadilan tidak hanya mengizinkan tetapi juga mengharuskan pengembangan aktif ‘teknik hukum administratif … [yang dirancang] untuk memberikan efek yang lebih besar dalam hukum domestik terhadap norma-norma hak asasi manusia internasional.’ 188 Karakterisasi Lord Bingham tentang keinginan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai bagian penting dari aturan hukum 189 mungkin juga menunjukkan bahwa pengadilan, sebagai penjaga hukum yang sah, harus secara positif berupaya untuk menciptakan ‘pijakan’ hukum umum baru untuk perjanjian yang tidak berbadan hukum.
Mengevaluasi kewajaran pandangan-pandangan ini berada di luar cakupan artikel ini. Untuk saat ini, poin terpenting adalah bahwa tentu saja tidak ada apa pun dalam prinsip-prinsip dasar konstitusional yang diuraikan di atas yang mengharuskan pengadilan untuk berusaha menekan peran hukum perjanjian yang tidak tergabung dalam penalaran hukum domestik. Memang benar bahwa pengadilan tunduk pada larangan konstitusional yang penting dalam hal perjanjian: mereka tidak dapat memperlakukan tindakan ratifikasi sebagai, dengan sendirinya, mengubah isi hukum domestik. Namun, tidak ada tanggung jawab yang sesuai untuk, dalam evolusi hukum umum, berusaha meminimalkan ruang hukum yang diciptakan oleh hukum domestik untuk perjanjian.
Dengan latar belakang ini dalam pikiran, sekarang berguna untuk beralih ke istilah ‘dualisme’ dan untuk bertanya, secara khusus, apakah istilah itu membantu atau menghalangi pemahaman tentang posisi konstitusional dasar ini. Sebuah pernyataan awal yang layak dibuat adalah bahwa asal-usul intelektual dari istilah tersebut akan membuatnya tidak mengejutkan jika tidak memberikan deskriptor yang sangat membantu dari hukum publik Inggris. Ini karena, meskipun prevalensinya meningkat dalam penalaran yudisial dalam beberapa tahun terakhir, 190 dan bahkan disebut sebagai ‘prinsip konstitusional fundamental’, 191 ‘dualisme’ tidak berasal sebagai istilah hukum Inggris. Memang, House of Lords pertama kali menggunakan bahasa itu hanya pada tahun 2001 dalam kasus terkenal R v Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex p Pinochet (No 1) . 192 Sebaliknya, itu adalah istilah yang telah dipinjam oleh pengadilan domestik dari literatur umum tentang hukum internasional. 193 Dalam literatur ini, ‘dualisme’ sering disandingkan dengan ‘monisme’ dan secara kolektif keduanya dikatakan menawarkan dua ‘pandangan dunia yang berbeda … tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum domestik’. 194 Menurut pandangan ‘dualis’, ‘hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang kewenangan hukum yang terpisah dan dikotomis’ dengan hukum internasional ‘mengatur perilaku antar-negara’ dan hukum domestik, ‘interaksi antara orang dan negara, atau orang satu sama lain’; 195 sedangkan ‘monisme’ ‘memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai sistem tunggal dan terpadu … yang validitas dan kewenangannya [berasal] dari satu sumber yang sama.’ 196 Perlu dicatat juga bahwa peminjaman istilah ‘dualisme’ oleh pengadilan terjadi pada saat, seperti yang dikatakan Janne E. Nijman dan Andre Nollkaemper, ‘semakin banyak ahli hukum ingin melepaskan diri dari dikotomi antara monisme dan dualisme, dengan menyatakan bahwa konsekuensi logis dari kedua teori tersebut bertentangan dengan cara kerja badan-badan internasional dan nasional.’ 197 Armin von Bogdandy, yang mengemukakan kritiknya dengan sangat kuat, menggambarkan monisme dan dualisme sebagai ‘zombie intelektual dari masa lalu [yang] harus diistirahatkan atau “didekonstruksi.”‘ 198
Mungkin karena sejarah ini, penggunaan istilah ‘dualisme’ dalam hukum kasus dan komentar Inggris agak licin, dan bahasanya dapat, dan memang, digunakan untuk merujuk pada berbagai gagasan hukum yang berbeda. Di beberapa tempat, istilah ini telah digunakan tidak lebih dari sekadar cara singkat untuk merujuk pada prinsip hukum, yang dibahas dalam bagian berjudul ‘Keberatan konstitusional terhadap RIPIT?’ di atas, bahwa pemerintah Inggris tidak memiliki kewenangan untuk mengubah hukum domestik secara sepihak, termasuk melalui ratifikasi perjanjian. Dalam kasus Heathrow Airport v HM Treasury , misalnya, 199 Pengadilan Banding mendefinisikan, apa yang digambarkannya sebagai, ‘prinsip konstitusional dualis’ dengan istilah berikut: ‘Eksekutif memiliki hak prerogatif untuk menyimpulkan perjanjian internasional, tetapi hak ini tidak dapat digunakan untuk mengubah hukum domestik … Oleh karena itu, fakta ratifikasi perjanjian oleh Eksekutif di tingkat internasional tidak berfungsi, dengan sendirinya, untuk menciptakan hak atau kewajiban di tingkat domestik.’ 200
Bagian ini menawarkan deskripsi yang sebagian besar akurat tentang prinsip hukum yang penting. Akan tetapi, tidak perlu menggunakan istilah ‘dualisme’ untuk mengungkapkannya. Memang, ‘dualisme’ tampaknya merupakan singkatan yang buruk karena penekanannya tidak pada tempatnya. ‘Dualisme’ mengomunikasikan gagasan tentang tingkat keterpisahan atau keterhubungan yang menjadi ciri hukum domestik dan internasional. Sedangkan inti dari prinsip yang dirujuk oleh Pengadilan Banding menyangkut sejauh mana kekuasaan eksekutif. Prinsip ‘tidak ada pembuatan hukum oleh eksekutif’ akan menjadi frasa yang lebih jelas daripada ‘dualisme’.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, pengadilan dan komentator Inggris terkadang menggunakan istilah ‘dualisme’ dengan cara yang lebih kuat. Yaitu, untuk merujuk pada gagasan bahwa hukum domestik dan hukum internasional harus dilihat sebagai sesuatu yang ada dalam ‘bidang yang independen’. 202 Dalam sidang Pengadilan Divisi Friends of the Earth , misalnya, Stuart-Smith LJ menjelaskan bahwa itu adalah konsekuensi dari ‘prinsip dualisme’ bahwa ‘hukum internasional dan hukum domestik dianggap sebagai sistem hukum yang terpisah, yang beroperasi pada bidang yang berbeda.’ 203 Penekanan pada ‘independensi’ dan ‘keterpisahan’ ini tidak menyenangkan karena dua alasan. Pertama, hal itu mengaburkan posisi hukum yang sebenarnya. Yaitu, bahwa prinsip-prinsip hukum Inggris membuat perjanjian relevan secara hukum dalam berbagai cara yang luas dan berkembang, yang RIPIT hanyalah salah satu ilustrasi penting dan terkini. Prinsip-prinsip ini berarti bahwa hubungan antara perjanjian dan hukum domestik dalam penalaran hukum, mungkin semakin, dicirikan oleh banyak keterkaitan, bukan keterpisahan. Kedua, menekankan independensi dan keterpisahan juga berisiko mengaburkan poin penting, yang ditekankan di atas. Yaitu, bahwa tidak ada prinsip konstitusional yang berlaku yang mengharuskan pengadilan untuk berusaha meminimalkan peran hukum perjanjian yang tidak tergabung dalam penalaran hukum domestik. Konsep ‘dualis’ berisiko membangkitkan citra spektrum keterpisahan, dengan setiap perkembangan oleh pengadilan ke atas spektrum menuju keterkaitan yang lebih besar antara hukum domestik dan internasional yang membawa sistem hukum semakin jauh dari asal-usul ‘dualis’-nya. Citra ini merupakan cerminan yang buruk dari posisi hukum dan konstitusional yang sebenarnya.
Oleh karena itu, secara keseluruhan, para hakim dan akademisi akan lebih baik jika mereka berbincang tentang hubungan antara perjanjian, hukum Inggris, dan pengadilan domestik tanpa menggunakan istilah ‘dualisme’. Istilah tersebut tidak hanya tidak diperlukan, tetapi juga akan mendorong ketepatan yang lebih tinggi dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip konstitusional dan hukum utama yang berlaku. Hal itu juga akan menghindari risiko bahwa gagasan yang salah – seperti promosi ‘keterpisahan’ antara hukum internasional dan domestik merupakan nilai tersendiri – akan memengaruhi penalaran yudisial.
KESIMPULAN: PROSPEK RIPIT DI MAHKAMAH AGUNG INGGRIS
Ada baiknya untuk menyimpulkan artikel ini dengan kembali ke pokok bahasan yang disampaikan dalam pendahuluan. RIPIT belum menjadi pokok bahasan banding di Mahkamah Agung Inggris. Beberapa orang mungkin menduga doktrin tersebut tidak akan diterima dengan baik di hadapan pengadilan tertinggi Inggris. Hal ini terjadi setidaknya karena dua alasan.
Pertama, Mahkamah Agung Inggris, dalam beberapa tahun terakhir, dikatakan menunjukkan ‘sikap hukum yang berbeda terhadap hukum internasional yang tidak berbadan hukum … yang lebih skeptis terhadap pengaruhnya dibandingkan dengan perwujudan sebelumnya.’ 204 Marcus Teo, misalnya, menggambarkan penalaran Pengadilan dalam kasus Law Debenture Trust baru-baru ini ditandai dengan ‘kecemasan yang mendalam tentang penggunaan hukum internasional dalam proses hukum di Inggris.’ 205 Pernyataan seperti itu menggambarkan Pengadilan sebagai pihak yang secara ideologis cenderung meminimalkan ruang yang disediakan untuk perjanjian dalam penalaran hukum domestik.
Akan tetapi, penting untuk menyadari bahwa kasus-kasus seperti Law Debenture Trust dan SC 206 menimbulkan pertanyaan tentang apakah hukum domestik mengharuskan pengadilan untuk memanfaatkan ketentuan perjanjian yang tidak berbadan hukum dengan cara-cara yang sangat spesifik . Dengan kata lain, ini adalah kasus-kasus tentang apakah hukum domestik memberikan ‘pijakan’ khusus untuk perjanjian yang diklaim oleh para pihak. Dalam keduanya, Mahkamah Agung Inggris menyimpulkan bahwa tidak demikian. Kesimpulan-kesimpulan ini jauh dari menentukan nasib RIPIT. RIPIT, sebagaimana yang dikemukakan dalam artikel ini, memang memiliki dasar doktrinal yang kuat dalam hukum domestik: ia memerlukan penerapan prinsip yang mapan dari tinjauan yudisial domestik – prinsip ABCIFER – pada jenis kebijakan tertentu.
Kedua, pengembangan RIPIT juga mungkin dianggap tidak sesuai dengan putusan terbaru Mahkamah Agung Inggris dalam R (A) v Secretary of State for the Home Department 207 ( A ), dan R (BF (Eritrea)) v Secretary of State for the Home Department 208 ( BF (Eritrea) ). Latar belakang kasus-kasus ini adalah serangkaian keputusan Pengadilan Banding yang memungkinkan pemohon untuk menantang dokumen kebijakan atas dasar bahwa dokumen tersebut menciptakan ‘risiko sistemik’ dari pengambilan keputusan yang gagal mematuhi hukum domestik. 209 Pengadilan dalam A menyimpulkan bahwa risiko sistemik merupakan dasar yang tidak tepat untuk peninjauan kembali yudisial. Sebaliknya, pasca- A , pengadilan peninjau yang dihadapkan dengan tantangan terhadap kebijakan yang dikatakan memberikan panduan yang tidak tepat kepada pejabat tentang cara mematuhi hukum, harus menanyakan apakah kebijakan tersebut dirusak oleh satu atau lebih dari tiga cacat berikut: (i) pencantuman ‘pernyataan positif hukum yang salah’, (ii) kegagalan perancang untuk mematuhi tugas untuk memberikan ‘nasihat yang akurat tentang hukum’ dan (iii) berpura-pura memberikan ‘pernyataan komprehensif tentang posisi hukum yang relevan’ dan gagal melakukannya. 210
Kasus-kasus ini dapat dilihat sebagai bagian dari tren yang lebih luas untuk menarik diri dari pengawasan yudisial yang ketat atas penggunaan kebijakan dalam pengambilan keputusan administratif. 211 Namun, yang terpenting, mereka juga tidak menghalangi Mahkamah Agung Inggris untuk mendukung RIPIT. Kerangka kerja yang diartikulasikan dalam A menetapkan keadaan di mana dokumen kebijakan akan melanggar hukum atas dasar khusus bahwa dokumen tersebut gagal mengarahkan pejabat secara akurat untuk bertindak sesuai dengan hukum domestik. Tiga kategori kesalahan yang diidentifikasi oleh pengadilan tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap dari keadaan di mana ketentuan kebijakan mungkin melanggar hukum secara lebih luas. Memang, Mahkamah Agung Inggris secara eksplisit menyoroti beberapa prinsip hukum lain yang juga berlaku untuk kebijakan dan dapat membuat ketentuannya melanggar hukum. 212 Oleh karena itu, mendukung RIPIT tidak akan bertentangan dengan A dan BF (Eritrea) . Itu hanya akan melibatkan pengakuan bahwa ada prinsip peninjauan yudisial yang lebih mapan, yaitu prinsip ABCIFER , yang juga harus dipatuhi oleh suatu kebijakan agar sah.
Oleh karena itu, diharapkan Mahkamah Agung Inggris akan mendukungnya jika menghadapi banding terkait RIPIT di tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, yang akan sangat berharga adalah jika pengadilan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh banding tersebut untuk mengklarifikasi dasar doktrinal RIPIT. Seperti yang dijelaskan dalam artikel ini, RIPIT tidak boleh dilihat sebagai perluasan dari prinsip Mandalia , tetapi sebagai penerapan prinsip ABCIFER . Akan sangat berharga juga jika pengadilan meninjau kembali beberapa cara umum untuk mengekspresikan hubungan antara perjanjian, hukum Inggris, dan pengadilan, termasuk dengan secara sadar mengalihkan wacana dari istilah ‘dualisme’ itu sendiri.

